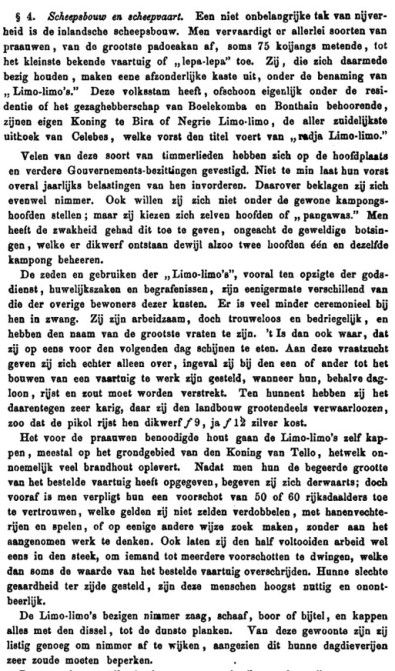"Mereka yang menyibukkan dirinya dengan [pembuatan perahu] merupakan sebuah kasta tersendiri, di bawah nama orang 'Limo-Limo'. Suku itu, meski sebenarnya berada di bawah residen atau pemerintahan Bulukumba dan Bonthain, dipimpin seorang raja tersendiri di Bira atau negeri Limo-Limo, di ujung paling selatan Celebes, yang bergelar 'Raja Limo-Limo'. Banyak dari pengrajin perahu itu bermukim di ibu kota [Celebes = Makassar] dan sekian banyak tempat di bawah pemerintahan Hindia-Belanda yang lain. […] Mereka tidak mau beratasan kepala kampung biasa, tetapi memilih tetua mereka, atau 'pangawa', sendiri. [...]
Adat-istiadat orang 'Limo-Limo', terutama dalam hal agama, pernikahan dan penguburan, agak berbeda daripada kebiasaan penduduk lain pesisir ini. Antara mereka terdapat jauh lebih kurang hal yang bersifat seremonial. Mereka rajin, tetapi susah dipercaya dan suka menipu, dan punya nama sebagai pemakan nan rakus. Dan memang benar bahwa mereka sepertinya pada satu kali makan sekaligus mau makan untuk besoknya pula. Mereka menyerah pada kerakusan makan itu hanya bila merak diperkerjakan untuk membangun perahu bagi seseorang, karena mereka, selain gaji harian, harus diberikan beras dan garam. Di tempat asalnya, mereka hidup dengan sangat sederhana, karena mereka tidak mengurusi pertanian, sehingga di sana sepikul beras sering dibayar 9, ya 12 gulden perak.